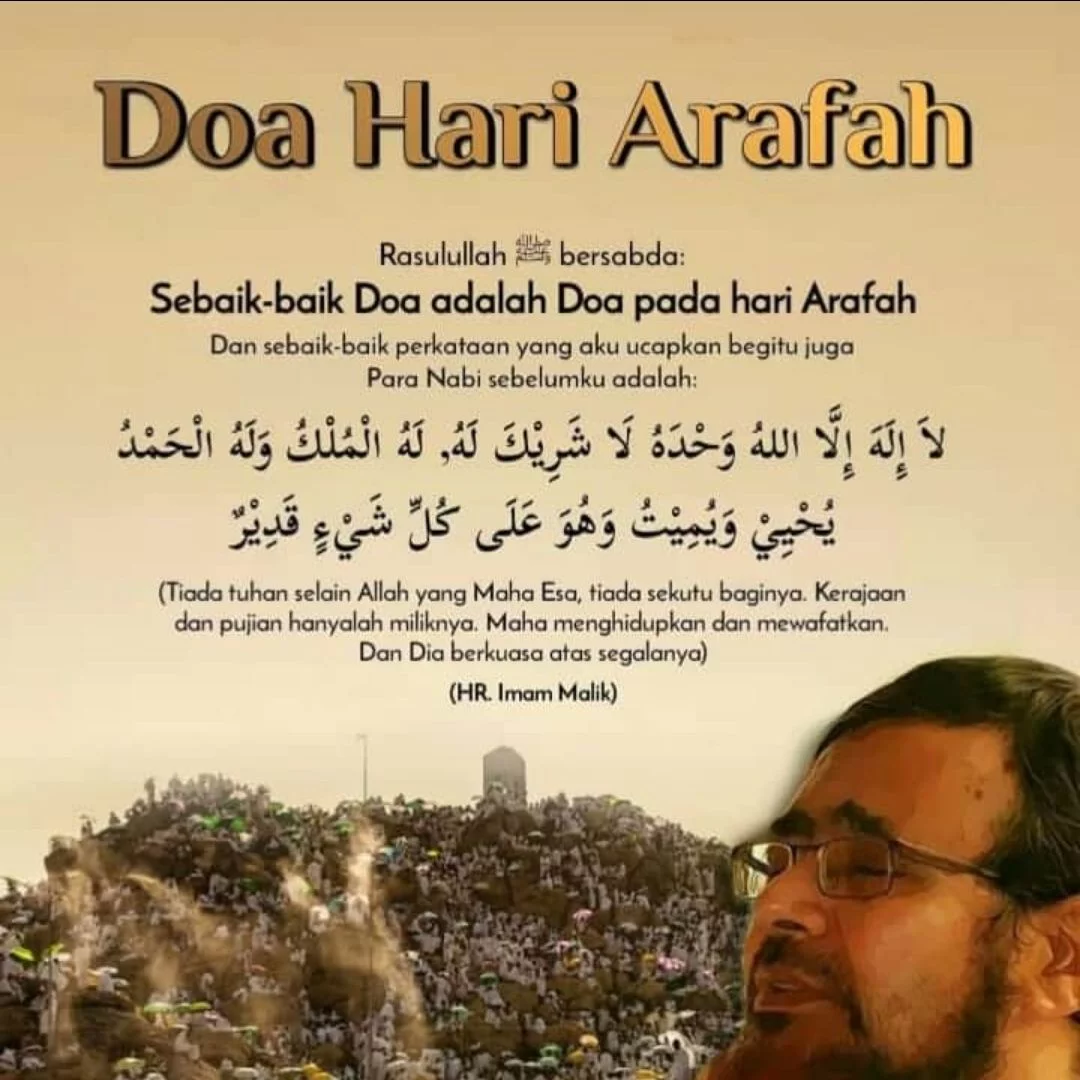Pelaksanaan 2 Hari Raya Idul Adha – Rasulullah memberi peringatan bahwa berpuasa dan berbuka dengan orang banyak karena berbeda-beda hari kurang beliau sukai. Jika tetap melakukannya juga, sebaiknya dilakukan dengan rahasia, bukan disiarkan.
Perbedaan penentuan hari raya Idul Adha yang menimbulkan dua hari raya Idul Adha bukan hal baru dalam sejarah Islam di Indonesia. Kasus ini pernah terjadi pada tahun 1973, bahwa pelaksanaan Idul Adha di Indonesia tahun 1973 (1392 H) terjadi pada 2 hari. Ada yang merayakan Idul Adha pada hari Ahad 14 Januari 1973; dan ada pula yang merayakannya pada Senin 15 Januari 1973.
Keputusan Departemen Agama
Menurut pengumuman resmi Dep. Agama kala itu, Idul Adha jatuh pada Senin 15 Januari 1973. Menariknya, putusan pemerintah ini sesuai dengan perhitungan hisab Muhammadiyah. Adapun yang melaksanakan hari raya Idul Adha pada hari Ahad (14 Januari 1973) di antaranya adalah Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. Bahkan, di Malaysia kala itu kabarnya juga diadakan pada hari Ahad juga.
Hari Wukuf di Arafah
Yang dijadikan acuan adalah keputusan Pemerintah Saudi Arabiyah yang mengatakan bahwa wuquf di Arafah jatuh pada hari Sabtu 13 Januari 1973, karena 1 Dzulhijjah ditetapkan pada 5 Januari 1972. Hari Senin tanggal 8 Desember 1975, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta menyiarkan berita di media-memdia Jakarta bahwa, Wuquf tahun itu jatuh pada hari Kamis tanggal 11 Desember 1975, sehingga orang-orang di Makkah mengerjakan Idul Adha hari Jumat 12 Desember 1975. Rabithah ‘Alam Islamiy di Makkah bahkan mengirim telegram kepada Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat di Jakarta, menyatakan tentang wuquf hari Kamis itu, dan bukan pada hari Jumat.
Menindak lanjuti keputusan dari Saudi, maka Dewan Da’wah Islamiyah Jakarta Raya bersama Ikatan Masjid Jakarta mengirim delegasi bersama untuk menemui Departemen Agama. Saat itu, delegasi diterima oleh Sekjen. Dep. Agama, Kol. Drs. H. Bahrum Rangkuti. Pada kesempatan itu diusulkan agar diupayakan agar Idul Adha disamakan baik pada tahun itu maupun yang akan datang berdasarkan wuquf di Arafah. Mengingat, hari Arafah itu hanya satu, dan terjadinya di Mekah. Usul itu pun disampaikan kepada Menteri Agama. Hanya saja, berdasarkan keputusan resmi, Hari Raya Idul Adha 1392 ditetapkan pada hari Senin 15 Januari 1973.
Sayangnya, tidak dijelaskan alasan penetapan tersebut. Akibatnya, pada saat itu ada 2 hari raya Idul Adha di Indonesia. Ada yang shalat id hari Ahad, ada pula yang menunaikannya pada hari Senin. Peristiwa ini sampai dimuat dalam Harian Masa Kini. Lalu bagaimana dengan sikap Seksi Falak PP. Muhammadiyah Majlis Tarjih melihat persoalan ini? Berikut ini akan diuraikan pandangan Muhammadiyah dalam peristiwa unik ini.
Dalam majalah Suara Muhammadiyah No. 3 (1973) ada tajuk “Sekitar 2 Hari Raja Idul Adha 1392”. Di situ dijelaskan latar belakang dan kronologi perbedaan itu terjadi. Bahkan dijelaskan pula pernyataa Seksi Falak Muhammadiyah terkait hal ini. Di antara pernyataan yang cukup mewakili, “Tidaklah mungkin menyamakan begitu saja hari yang ada di Makkah dengan hari yang ada di Indonesia untuk menentukan Hari Raya Idul Adha. Jadi jalan yang paling aman, ilmiyah dan syar’iyah, untuk menentukan permulaan bulan dan termasuk juga Hari Raya Idul Fithri ataupun Idul Adha adalah dengan hisab.”
Ada beberapa pertimbangan yang melatari pernyataan tersebut. Pertama, Hari Ahad di Indonesia mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam WIB sama dengan hari Sabtu (Hari Arafah) 1973 untuk wilayah Indonesia. Sedangkan Hari Arafah yang ditetapkan jatuh pada hari Sabtu untuk Makkah tidak seluruhnya bertepatan selama 24 jam dengan hari Sabtu yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, tidak bisa ditetapkan begitu saja bahwa Idul Adha mesti harus sama dengan di Makkah. Kedua, berdasarkan hasil hisab Muhammadiyah yang menetapkan hari Senin sebagai hari Raya Idul Adha.
Ketiga, seandainya Hari Raya Idul Adha ditetapkan di Indonesia pada Ahad 14 Januari 1973, perlu diperhatikan bahwa hari Arafah yang ditetapkan pada hari Sabtu di Makkah tidak seluruhya congruent (sama serupa) selama 24 jam dengan hari Sabtu di Indonesia. Apabila hari Sabtu ditetapkan begitu saja di Indonesia sebagai hari Arafah, maka konsekuensinya orang Indonesia mendahului 4 jam dari waktu orang di Mekah.
Itulah pandangan Tim Hisab atau Falak Muhammadiyah menghadapi perbedaan penentuan Hari Raya pada tahun 1973 (1392). Meski di kalangan umat Islam Indonesia ada perbedaan, hari raya Idul Adha tetap berlangsung dua hari (Ahad dan Senin). Semua berjalan lancar dengan penuh toleransi. Muhammadiyah dan Pemerintah tetap melaksanakan Idul Adha hari Senin; sedangkan Dewan Da’wah Islamiyah dan yang setuju dengannya tetap melaksanakan Idul Adha pada hari Ahad.
Menariknya, dalam buku “1001 Soal Kehidupan” (2016) karya Buya Hamka, beliau pernah ditanya mengenai hari raya Idul Adha 1975 (1395), intinya: “Mesti Samakah Hari Raya dengan Mekah?” Mengingat pada tahun itu, Departemen Agama memutuskan Idul Adha jatuh pada Sabtu 13 Desember 1975. Sedangkan di Saudi kala itu, ditetapkan bahwa wuquf di Arafah jatuh pada hari Kamis (11 Desember 1975) sehingga Hari Idul Adha di Mekkah adalah Jum’at 12 Desember 1975.
Melihat peristiwa ini, yang ditanyakan kepada Hamka, sahkah shalat hari raya Idul Adha pada Sabtu 13 Desember 1975 padahal sudah ada berita wuquf pada hari Kamis di Makkah sehingga seharusnya hari raya jatuh pada hari Jum’at? Cukup panjang jawaban Hamka yang coba saya tuliskan semuanya, berasal dari http://buyahamka.org/tanya-jawab/mesti-samakah-hari-raya-dengan-di-mekkah/.

Mesti Samakah Hari Raya Dengan di Mekkah
Pertanyaan:
- Menurut keputusan dari Departemen Agama R.I., Hari Raya ‘Iedul Adha 1395 jatuh pada hari Sabtu 13 Desember 1975. Keputusan itu dikeluarkan setelah Departemen Agama menerima laporan dari ahli-ahli hisab dan kesaksian orang-orang yang mengadakan ru’yah bil fi’li (melihat hilal dengan perbuatan). Terdapat kesamaan hasil Hisab dengan hasi Ru’yah, bahwa akhir Zulqa’idah jatuh pada hari Rabu sore 3 Desember 1975.
- Tiba-tiba pada hari Senin tanggal 8 Desember 1975, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta menyiarkan berita di suratkabar-suratkabar Jakarta bahwa, Wuquf tahun ini jatuh pada hari Kamis tanggal 11 Desember 1975, sehingga dengan demikian dengan sendirinya orang-orang di Mekkah mengerjakan sembahyang ‘Iedul Adha pada hari Jum’at 12 Desember 1975. Kabarnya, Rabithah ‘Alam Islamiy di Mekkah mengirim telegram pula kepada Dewan Da’wah Islamiyah Pusat di Jakarta, menyatakan tentang wuquf hari Kamis itu, dan bukan pada hari Jum’at.
- Lantaran itu timbullah dua macam tanggapan tentang kejadian ini, yaitu ada golongan yang menganjurkan agar Hari Raya jatuh di hari Jum’at, sebab kita telah mendapat keterangan yang pasti bahwa Wuquf adalah pada hari Kamis, bukan Jum’at seperti disangkakan semula. Tetapi ada yang berkeras mempertahankan keputusan semula, yaitu Sembahyang Hari Raya pada Hari Sabtu 13 Desember 1975. Menteri Agama juga memperkuat lagi keputusan Sembahyang Hari Raya hari Sabtu itu, setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Majelis Ulama dan ahli-ahli Hisab dan Ru’yah.
Sekarang saya bertanya, “Sahkah sembahyang Hari Raya hari Sabtu 13 Desember itu?”. Padahal telah datang berita pasti dari Mekkah bahwa Wuquf di Arafah hari Kamis.
Jawab:
Jika bersatu permulaan puasa, Hari Raya ‘Iedul Fitri dan Hari Raya ‘Iedul Adha di seluruh dunia Islam, sehingga sama puasa kaum Muslimin, sama berbuka dan sama Hari Raya Haji, adalah satu hal yang sangat baik sekali. Apatah lagi di zaman sekarang dengan adanya alat-alat telekomunikasi yang cepat dapat menyampaikan berita di seluruh dunia, hal yang semacam itu mungkin bisa dicapai.
Itulah sebab maka Jumhurul Ulama memandang bahwa persatuan umat dalam mengerjakan lbadat Puasa dan Hari Raya adalah sangat dituntut.
Tetapi oleh karena perkembangan yang terjadi dalam Dunia Islam dalam masa 14 abad, dan mengingat pula sabda Nabi SAW:
” Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia sendiri akan dikalahkan ( semakin berat dan sulit )…”
Maka timbullah pendapat bahwa persatuan mengerjakan puasa, dan dua Hari Raya itu sukarlah akan tercapai. Sebab itu maka yang sama pendapat Ulama tentang wajibnya persamaan puasa dan dua Hari Raya itu hanyalah pada negeri-negeri yang berdekatan saja, yaitu yang satu mathla’-nya. Adapun yang berjauhan mathla’ sebagaimana antara Andalus (Sebelah Barat) dan Khurasan (Sebelah Timur) tidaklah dapat dipersamakan.
Pendapat ini menjadi kuat pula karena ada dalil Hadits yang pernah kejadian di zaman sahabat-sahabatRasulullah. Yaitu sebuah Hadits yang dirawikan oleh Kuraib bahwa dia datang ke Syam. Ia sampai di sana di akhir bulan Sya’ban menjelang masuk bulan Ramadhan. Dan dia sendiri turut melihat (rukyah) bulan sabit (hilal) ketika dia berada di Syam.
Dia (Kuraib) berkata,”Saya melihat bulan itu pada malam Jum’at”. Setelah beberapa hari di Syam dia pun kembali ke Madinah di ujung bulan Ramadhan. Dia berkata, “Lalu bertanya kepadaku Ibnu Abbas dan dibicarakannya juga soal hilal itu. Dia bertanya,”Bila kalian melihat Hilal?” Saya jawab, “Malam Jum’at”. Lalu lbnu Abbas bertanya lagi,”Engkau sendiri melihat?” Kuraib menjawab, “Ya, saya lihat sendiri dan orang banyakpun melihatnya pula, maka puasalah orang banyak pada besoknya dan begitupula Mu’awiyah.”
Lalu lbnu Abbas berkata, ”Tetapi kami melihat Hilal itu pada malam Sabtu”, dan kami teruslah puasa sampai kami cukupkan bilangan tiga puluh hari, atau kami lihat Hilal nanti”.
Lalu Kuraib bertanya: “Tidakkah kalian padukan saja dengan rukyah Mu’awiyah dan puasanya.”
Ibnu Abbas menjawab, “Tidak. Karena begitulah diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita.” Hadits ini disalin secara bebas oleh penulis, dirawikan oleh Imam Ahmad, Muslim dan At- Tirmidzi.
At-Tirmidzi menyatakan tentang Hadits ini, ”Hadits ini adalah Hasan, Shahih dan Gharib. Dan amalan adalah menurut Hadits ini pada sisi ahli ilmu, yaitu bahwa tiap-tiap negeri dengan rukyahnya sendiri.”
Hadits inilah yang menjadi pegangan seluruh dunia Islam yang bukan lagi semata-mata di tanah Arab, melainkan telah melebar meluas ke luar Arab, bahkan ke seluruh dunia.
Melihat Bulan
Berdasar kepada Firman Tuhan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 189 :
“Mereka bertanya kepadamu tentang hilal (bulan sabit). Katakanlah: ‘Bulan sabit itu adalah penentu waktu bagi manusia dan (bagi penentuan waktu ibadah) haji. ‘
Berdasarkan kepada ayat Al-Qur’an ini, maka pokok pertama dan utama dalam memulai ibadat, baik ibadat puasa Ramadhan atau penutupan puasa Ramadhan (Iedul Fithri) atau penentuan permulaan Hajji, ataupun menentukan perhitungan mengeluarkan zakat (haul),-Semuanya dihitung menurut bulan Qamariah, bukan Syamsiah.
Caranya ialah apabila ada orang yang melihat hilal (yaitu bulan Sabit, permulaan bulan baru di ufuk Barat, sesudah terbenam matahari), lalu dilaporkannya pada yang berwenang atau penguasa di negeri itu. Sesudah memeriksa keterangan- keterangan yang diberikan oleh yang melihat bulan itu dengan menyuruhnya mengucapkan dua kalimah syahadat lebih dahulu setelah penguasa mempercayai berita itu, lalu disuruhlah menyiarkan berita itu kepada orang banyak dan dimaklumkanlah bahwa besoknya mulailah puasa, ataubesoknya; mulailah Hari Raya ‘Iedul Fithri.
Kala bulan Hajji, dilihat orang pula hilal permulaan Zulhijjah dan dilaporkannya kepada penguasa, lalu dimaklumkanlah ke muka umum bahwa Hari Raya Hajji akan jatuh pada 10 hari sesudah itu.
Adapun di Mekkah sendiri ada tambahan khusus lagi, yaitu bahwa pada sembilan hari bulan akan wuquf di ‘Arafah.
Cara yang begini adalah menurut Sunnah dari Nabi sendiri. Yaitu sebuah Hadits Ibnu Abbas yang dirawikan oleh At-Tirmidzi bahwa pada suatu hari seorang A’raby/Badui datang memberitahukan bahwa dia melihat hilal malam itu. Lalu dia disuruh mengucap dua kalimah syahadat, (suatu kesaksian yang lebih besar pengaruhnya dari pada sumpah itu sendiri bagi orang yang beriman; bahwa dia bertanggung jawab sebagai Muslim dan ucapan yang dia keluarkan). Setelah Nabi percaya kepada kesaksian orang itu, baginda bersabda kepada Bilal.
“Hai Bilal. Beritahukan kepada manusia agar berpuasa besok”.
Sebuah lagi pula Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa pada satu waktu di akhir bulan Ramadhan datang dua orang Badui menyatakan bahwa mereka berdua melihat bulan kemarin sore (senja). Lalu Nabi menyuruh semua orang melepaskan puasanya di hari itu. Dan karena hari sudah siang, sembahyangnya besok saja.
Meskipun yang melihat hanya satu orang kampung (orang desa/orang Badui) atau dua orang, namun apabila penguasa telah percaya akan keterangannya, disampaikanlah hal itu kepada orang banyak. Cara sekarang disampaikanlah dengan perantaraan alat-alat telekomunikasi: telegram, telepon, televisi, radio, surat-surat kabar dan lain-lain. Kalau cara dulu-dulu ialah dengan memukul tabuh atau beduk, atau dipukulkan canang.
Maka orang banyakpun wajiblah menuruti perintah itu, tidak boleh menantangnya lagi. Karena sabda Nabi SAW:
“Puasalah kamu ialah di hari kamu semua berpuasa, berbuka kamu ialah di hari kamu semuanya berbuka, menyembelih korban kamu ialah di hari karnu semuanya menyembelih korban.”
Hadits ini dirawikan oleh At-Tirmidzi dan lbnu Majah dan Abu Dawud.
Di Hadits yang lain dijelaskannya lagi:
“Puasa ialah di hari kamu semuanya puasa, Iedul Fithri ialah di hari kamu berbuka, ‘ledul Adha ialah di hari kamu semua berkorban.”
Berkata lbnu Taimiyah dalam Fatwanya:
Artinya: Setengah ahli ilmu dalam hal Hadits menafsirkan maksud Hadits-Hadits ini ialah bahwa baik berpuasa ataupun berbuka hendaklah bersama jama’ah, golongan yang terbesar dari orang banyak.
Sehingga Imam Syafi’i berpendapat bahwa seorang yang telah melihat bulan seorang dirinya, belum sempat ia menyampaikan kepada penguasa, dia boleh puasa atau berbuka secara rahasia, agar jangan mengganggu orang banyak.
Niscaya wajiblah seorang yang jelas melihat Hilal menyampaikan kepada yang berwenang. Kalau keterangannya tidak dipercayai, sedang dia yakin telah melihat bulan, bolehlah dia puasa atau berbuka sendiri secara rahasia.
Hikmatnya tentu supaya jangan merusak suasana jama’ah kaum Muslimin.
Dari dalil-dalil sunnah Nabi itu teranglah bahwa mengerjakan ibadat puasa atau Hajji itu dengan berjama’ah. Yang dimaksud dengan jama’ah ialah masyarakat kaum Muslimin. Di zaman Rasulullah masih hidup, pimpinan jama’ah itu adalah di tangan baginda sendiri.
Dan setelah Rasulullah wafat ialah di tangan khalifah-khalifah yang menggantikan baginda. Dan setelah dunia Islam bertambah luas dan berkembang maka jama’ah kaum Muslimin itu dikepalai oleh Amir-amir atau Sultan-sultan di daerahnya masing-masing. Setelah kebanyakan negeri Islam dijajah oleh bangsa Barat, terutama sebagai di Indonesia ini terserah kepada kaum Muslimin sendiri mengatur permulaan puasanya dan berbukanya dan Hari Raya Hajji-nya.
Di negeri-negeri yang ada raja atau Sultan dalam naungan penjajah, raja-raja dan Sultan itulah yang menentukan puasa dan berbuka dan Hari Raya Hajji. Sebab itu sebagai di Sumatera Timur di zaman jajahan, tidaklah mustahil jika berbeda permulaan dan penutupan puasa di antara kerajaan Deli dengan Kerajaan Serdang, Kerajaan Asahan dengan Kerajaan Kualuh, walaupun “Kerajaan-Kerajaan” itu sangat berdekatan saja. Adapun di luar daerah kekuasaan Sultan, seumpama kota Medan orang tidak merasa terikat oleh perintah Sultan. Sebab itu penentuan puasa, berbuka dan hari Raya Hajji adalah menurut almanak yang mereka percayai dan pegangi saja. Lebih-lebih setelah berkembang ilmu Hisab, mulailah banyak orang yang puasa, berbuka dan hari Raya Hajji menurut hisab saja. Perkumpulan-perkumpulan Islam seperti Muhammadiyah mengeluarkan pengumuman tiap tahun yang dijadikan pegangan oleh anggotanya dan orang yang menuruti faham yang diajarkannya.

Kementrian Agama
Sebagai hasil perjuangan membentuk sebuah Negara merdeka yang berdaulat pada tahun 1945, Kaum Muslimin Indonesia berhasil memperjuangkan sehingga terbentuklah dalam susunan Pemerintahan Republik Indonesia suatu Kementerian bernama Kementerian Agama (kemudian disebut Departemen Agama). Departemen inilah yang dalam masa 30 tahun sejak Proklamasi kemerdekaan berusaha menentukan hari resmi keagamaan Republik Indonesia, termasuk permulaan puasa, hari Raya ‘Iedul Fithri dan Hari Raya ledul Adha, bahkan juga permulaan tahun Hijrah.
Buat menyatukan yang serentak rupanya tidaklah semudah yang disangka. Sebab sudah bertahun-tahun lamanya masing-masing golongan mengambil keputusan sendirinya, ada yang menurut rukyah dan ada yang menurut hisab, dan masing-masing menganjurkan kepada pengikutnya agar berpuasa, berbuka dan berhari Raya menurut “keputusan organisasi kita.”
Kadang-kadang Hari Raya itu dijadikan ukuran untuk menguji sampai berapa besar pengaruh kita.
Apa yang jadi sebab selisih di antara ulama-ulama zaman dahulu, sebagai Imam Mujtahid yang berempat, agar penguasa negaralah yang memutuskan hari berpuasa dan berbuka dan berhariraya itu ditaati, dan barang siapa yang tidak yakin akan keputusan penguasa itu, bolehlah berpuasa atau berbuka sendiri secara rahasia (lmam Syafi’i), tidaklah dituruti lagi.
Orang berpegang kepada demokrasi cara Barat bahwa semua orang bebas melakukan ibadat menurut keyakinan masing-masing.
Kadang-kadang kalau bertemu Menteri Agama yang bijaksana, mereka panggillah ulama-ulama dan pemuka-pemuka pergerakan Islam bermusyawarat menentukan hari berpuasa atau berbuka itu. Seorang Menteri lagi mengerahkan orang di tiap-tiap daerah pergi melakukan melihat bulan (rukyatul hilal bil fi’li). Tetapi ada pula Menteri yang tidak, mempedulikan Musyawarat Ulama atau memerintah orang melihat bulan, tetapi memaksakan orang banyak agar mengikuti faham golongan yang dianutnya dan memandang “anti nasional” barang siapa yang menganjurkan puasa atau berbuka menurut pegangan golongannya pula. Sehingga pernah kejadian seorang Menteri Agama menganjurkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan agar menangkap dan menahan seorang yang dianggapnya “menentang” keputusannya tentang puasa dan Hari Raya itu. Kejadian ini di tahun 1962.
Kemudian di tahun 1964 berhasil juga memencilkan orang ini dari masyarakat, setelah difitnah memberikan kuliah di IAIN Ciputat yang berisi hasutan kepada mahasiswa supaya meneruskan perjuangan Karto Suwiryo. Setelah ditahan 2 tahun empat bulan barulah dilepaskan.
Karena ternyata tidak ada bukti buat dituntut di muka pengadilan. Tetapi maksud sudah tercapai. Yaitu dia ditahan dan didiamkan 28 bulan.
Tetapi Menteri Pertahanan dan Keamanan tersebut mengirim orang kepada yang diusulkan supaya ditangkap itu hati-hati dan keinginan Menteri Agama itu tidaklah dilaksanakan oleh Menteri Keamanan tersebut.
Begitulah keadaan di Indonesia bertahun-tahun, sehingga suasana permulaan puasa, dan yang berkesan ialah tentang Hari Raya ledul Fithri, waktu itu selalu suasana pikiran jadi keruh, karena bertikainya Hari Raya.
Setelah Prof. Dr. A, Mukti Ali naik menjadi Menteri Agama, beliau telah mengambil satu kebijaksanaan. Yaitu mendirikan sebuah Panitia tetap ahli Rukyah dan Hisab. Yang duduk dalam Panitia tersebut ialah ahli-ahli hisab dari sekalian golongan yang memakai hisab dan golongan yang mempertahankan rukyah. Supaya setiap tahun diadakan hisab dan rukyah dan dijadikan di antara keduanya sokong-menyokong. Karena hisab yang teliti dapatlah menjadi penuntun untuk melakukan rukyah. Dan rukyah yang benar-benar jujur dapat jadi kontrol atas ketelitian hisab.
Sejak Panitia itu terbentuk, jadi tambah intensiflah usaha mempersatukan permulaan puasa dan hari raya itu. Meskipun “kedaulatan” golongan-golongan yang telah tumbuh dengan suburnya di zaman penjajahan itu sangat sukar untuk disatukan ke dalam satu wadah, yaitu wadah penguasa. Dan meskipun Departemen Agama itu adalah hasil perjuangan Kaum Muslimin sendiri.
Namun dua tiga tahun terakhir ini “kehangatan’ perbedaan Hari Raya itu sudah dapat diperkecil karena timbulnya kesadaran dengan adanya Panitia tetap itu.
Instruksi dari Mekkah
Sekarang timbul soal baru. Yaitu oleh karena telah serba cepatnya alat telekomunikasi, dengan adanya berita radio, dapatlah diketahui bahwa sudah kerap kali Puasa Ramadhan terdahulu di Mekkah satu hari. Kemudian di tahun 1395H ini terang sekali bahwa wuquf jatuh pada hari Kamis, sehingga sembahyang Hari Raya ‘Iedul Adha di Mekkah jatuh pada hari Jum’at. Sedangkan di Indonesia telah dilakukan rukyatul hilal bil fi’li; ternyata bahwa akhir Dzulka’idah jatuh pada senja hari Rabu 3 Desember 1975.
Oleh karena hasil rukyah yang bersamaan dengan hasil hisab itu telah pasti bahwa 1 Zulhijjah 1395 jatuh hari Kamis 4 Desember 1975, maka Departemen Agama pun mengeluarkan maklumatnya, berdasar wewenang yang ada padanya, bahwa 10 Zulhijjah, hari untuk sembahyang Hari Raya Iedul Adha jatuh pada hari Sabtu 3 Desember 1975.
Dan ini diterima dengan lega oleh kaum Muslimin. Dan ini telah sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang kita salinkan di atas tadi. Yaitu, “Puasa kamu ialah di hari kamu semua berpuasa. Berbuka kamu ialah di hari kamu semua berbuka dan Hari Raya Qurban kamu ialah di hari kamu semua berqurban.”
10 Zulhijjah disebut juga “Yaumun Nahr” (Hari Berqurban). Lantaran itu tidaklah wajib bagi kita meninggalkan maklumat yang timbul dari wewenang Menteri Agama, yang menyiarkan hasil rukyah dan hisab yang jelas itu, untuk disamakan dengan Hari Raya Hajji di Mekkah, yang menurut perhitungan hisab dan rukyah mereka, mereka lakukan pada 10 Zulhijjah juga.
Tidaklah berdosa orang yang berhari Raya Adha hari Sabtu, karena mereka mematuhi maklumat pemerintahnya yang berdasarkan hasil penyelidikan seksama itu. Dan tidaklah mesti hasil rukyah dan hisab di Indonesia sama harinya, oleh sebab Wuquf di ‘Arafah Hari Kamis.
Semua tahu tempat wuquf hanya satu di dunia; yaitu Arafah.
Kalau penguasa di sana telah memutuskan wuquf di ‘Arafah hari Kamis, wajiblah bagi orang yang hendak naik Hajji tahun itu mentaati keputusan penguasa di sana, turut wuquf hari Kamis. Tidak sah jika mereka wuquf hari Jum’at. Orang- orang, walaupun pemerintahnya memutuskan ‘ledul Adha hari Sabtu 13 Desember jika mereka sedang berada di Mekkah, wajiblah mereka turut wuquf hari Kamis. Tetapi kita di Indonesia yang tidak pergi hajji (wuquf) tidak wajib (tidak sunat) sembahyang hari Raya Adha hari Jumat. Melainkan tetap mematuhi keputusan penguasa kita.
Barulah wajib kita mengikuti segala keputusan dari Mekkah itu apabila “Seluruh dunia Islam telah memutuskan”, misalnya dalam satu Kongres Islam yang dihadiri oleh mereka yang berwenang, di sana diputuskan bahwa mulai waktu itu memulai puasa, menentukan Hari Raya Iedul Fithri dan ‘Iedul Adha hendaklah menurut apa yang diputuskan dari Mekkah. Dan dengan demikian hasil rukyah dan hisab kita tidak perlu lagi.
Kalau tidak demikian, maka tidaklah salah orang yang setia dan yakin memegang ilmu pengetahuan rukyah dan hisab dalam negerinya sendiri yang dikuatkan oleh pemerintahnya. Bagaimana akan memajukan hari Rayanya dari Sabtu ke Jum’at, karena berita dari Mekkah, sedangkan dunia Islam belum lagi memutuskan bahwa seluruh kaum Muslimin dan Negeri-negeri Islam menyerahkan menentukan puasa, berbuka dan hari Raya Hajji kepada Pemerintah Saudi.
Hadits yang dirawikan dari Kuraib oleh Imam Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, bahwa Ibnu Abbas sebagai Ulama Shahaby yang terbesar di Madinah di kala hidupnya, telah menyatakan bahwa mereka di Madinah tidak mengikuti permulaan puasa di Syam (Damaskus) dengan ucapannya, “Demikianlah kami disuruh oleh Nabi SAW.”
Padahal setelah dipelajari dalam sejarah, waktu kejadian itu ialah setelah perjuangan Ali bin Abi Thalib runtuh dan Mu’awiyah menang.
Mu’awiyah yang dahulunya hanya semata-mata ‘Aamir di Syam, dengan sebab kalahnya percaturan politik Abu Musa Al-Asy’ariy wakil ‘Ali menghadapi siasat Amr bir ‘Ash wakil Mu’awiyah, maka teguhlah Mu’awiyah jadi khalifah dan memakai gelar Amirul Mukminin dan berkedudukan di Syam. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Mu’awiyah pada tahun 40 Hijriyah, terjadilah perdamaian dan dinamailah tahun 40 Hijriyah sebagai “Tahun Jama’ah”, karena kaum Muslimin telah bersatu kembali. Setelah itu, maka Ibnu Abbas yang tadinya termasuk golongan Ali, mengundurkan diri dari politik dan mengakui kekuasaan Mu’awiyah. Dia menetap di Madinah beberapa waktu lamanya, kemudian pindah ke Mekkah dan akhirnya ke Thaif. Di Thaif itulah beliau wafat pada tahun 70 Hijriyah.
Sudah jelas bahwa Ibnu Abbas mengakui bahwa kekuasaan tertinggi telah di tangan Mu’awiyah dan dia wajib ta’at. Tetapi oleh karena permulaan puasa di Syam tidak mesti diikuti di Madinah, tetaplah beliau memulai puasa hari Sabtu setelah rukyah malam Sabtu di Madinah, meskipun Mu’awiyah memulai puasa hari Jum’at karena terlihat bulan malam Jum’at di Syam.
Sebab itu kalau misalnya Dunia Islam sepakat menyerahkan kekuasaan menentukan permulaan puasa atau berbuka atau Hari Raya Hajji diserahkan saja kepada Pemerintah Saudi, artinya ialah bahwa kaum Muslimin melepaskan hak yang telah diberikan kepada mereka oleh Syara’, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perlainan mathla’ di antara negeri-negeri yang berjauhan menyebabkan tidak wajib negeri yang jauh itu menuruti yang terlebih dahulu melihatnya.
Kesimpulan :
- Tidak wajib negeri yang berjauhan mengikuti puasa dan berbuka dan Hari Raya Hajji, karena mathla’ tidak sama.
- Wuquf di Arafah wajib dituruti menutup keputusan pe-nguasa di negeri itu.
- Rasulullah SAW memberi ingat bahwa kita puasa, berbuka dan berkorban menurut orang banyak. Berbeda-beda hari tidak beliau sukai. Kalau tidak yakin boleh lakukan terlebih dahulu atau lebih belakang tapi dengan rahasia.
- Seyogianya demi kesadaran kita beragama, kita berusaha mempersamakan Hari Raya Fithri dan Adha di masyarakat yang dekat, demi syiar Islam.
- Kebebasan beragama ala demokrasi Barat jelas tidak cocok dengan Hadits ini, “Puasa kamu di hari kamu semua berpuasa, dan seterusnya dan seterusnya.”
Kalau ada Ulama yang maju memberikan nasehat kepada Pemerintah agar tetap menuruti hasil rukyah bil fi’li ahli-ahli rukyah di Indonesia dan kesamaan pendapat ahli-ahli hisab, baik dari Muhammadiyah atau dari Nahdatul Ulama atau hasil Hisab UNISBA Bandung dan IAIN Imam Bonjol Padang dan tidak mereka anjurkan supaya mengikuti saja bunyi telegram dari Pemerintah Saudi Arabia atau Rabithah Alamil Islamy, tidaklah mereka berbuat yang baru dan melanggar.
Melainkan sudah berlaku pengunduran Hari Raya ‘ledul Fithri satu hari di belakang di zaman Nabi sendiri, karena baru siang itu dapat berita ada orang melihat Hilal kemarin petang. Dibukakan puasa di hari itu, lalu dilakukan shalat ‘Iedul fithri pada besoknya (karena hari sudah siang). Jadi ini bukti bahwa tidak mutlak mesti hari itu juga hari berbuka dan hari itu juga mesti sembahyang Hari Raya. Atau hari Kamis Wuquf di Arafah dan mesti hari Jum’at orang Hari Raya Qurban di Indonesia.
Hal itu terjadi karena pertimbangan-pertimbangan yang ada dasarnya. Oleh sebab itu Ibnu Hazm Al-Andalusy memberikan pendapat yang positif yaitu, “Barangsiapa yang tidak keluar pada hari Al-Fithri (berbuka) dan Hari Adha (berqurban) untuk mengerjakan sembahyang dua hari Raya, bolehlah dia keluar menyembahyang keduanya di hari kedua. Dan orang yang tidak keluar pagi-pagi benar, keluarlah sebelum matahari tergelincir, karena demikian itu adalah perbuatan yang baik. Dan Tuhan berfirman, “waf’alul khaira” – “Perbuatlah kebaikan”.
Lalu beliau kemukakan sebagai alasan Hadits orang-orang berkendaraan yang datang kepada Nabi mengatakan mereka melihat hilal kemarin sore, lalu Nabi menyuruh berbuka puasa di hari itu dan sembahyangnya besok.
Kemudiannya Ibnu Hazm menukilkan pula pendapat Imam Abu Hanifah bahwa orang yang tidak ke luar di hari kedua (2 Syawal atau 11 Zulhijjah) lalu dia keluar sembahyang Hari Raya di hari ketiga; Perbuatan itu adalah “Fi’ul Khairin” (perbuatan baik); tidak ada larangan padanya. (Lihat Al Muhalla dari Ibnu Hazm, Jilid V, hal 92 cetakan Beirut).
Bagi orang yang mempelajari soal ini sampai kepada dasarnya, menurut ilmu Fiqhi tidaklah mereka akan merasa ganjil kalau Keputusan Departemen Agama, Hari Raya dan Sembahyang Iedul Adha tetap pada hari Sabtu Desember itu. Soal ini hanya akan disebutkan oleh orang yang sengaja membesarkan mesti harus Jum’at demi mengikuti Mekkah karena persatuan berhariraya yang ingin di capai itu adalah sangat berlawanan dengan “kebiasaan” selama ini. Dengan tidak bertikainya Hari Raya dapat dihimpun dan dijaga kekompakan (perpaduan) golongan.
Yth. Saudara Dr. H. Zubair Usman dalam kedudukan beliau sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Muhammadiyah menulis dalam harian “Sinar Harapan” satu karangan yang isinya meminta pertanggunganjawab Majelis Ulama, mengapa memberi nasihat kepada Pemerintah supaya tetap hari Sabtu berhariraya, padahal telah ada berita dari Mekkah bahwa Wuquf hari Jum’at.
Hendaknya pertanyaan itu terlebih dahulu beliau hadapkan kepada Muhammadiyah Pusat sendiri, mengapa tidak pindah ke hari Jum’at, atau teman-teman beliau H. Sa’aduddin Jambek, salah seorang tokoh Pendidikan (Tarbiyah) Muhammadiyah, mengapa beliaupun menguatkan Hari Sabtu.
Atau lebih baik beliau serahkan soal ini kepada ahlinya. Karena kesarjanaan kita masing-masing adalah dalam bidang kita masing-masing. [ ] Selesai.
Wallahu a’lam bish shawab.
Sumber: Hidayatullah.com, buyahamka.org
Artikel terkait
- Benarkah Penentuan Shaum Arafah dan Idul Adha dengan patokan Wukuf di Arafah?
- Adam, Hawa dan Padang Arafah